“Rafi ayo bangun, solat subuh dulu!” ujar Bi Heni membangunkan putra sulungnya yang duduk di kelas 1 SMP.
“Masih ngantuk Mak!” balasnya.
“Anak santri gak boleh malas solatnya.” Timpal ibunya.
Dengan mata yang masih rapat anak sulungnya mencoba membangkitan badan, pergi keluar berpayung dalam hujan untuk berwudhu.
Bulir hujan dari mega hitam berlomba membasahi bumi, menawarkan hawa dingin dalam lorong pagi yang sepi. Sang waktu terus meloncat meninggalkan detik demi menit.
“Rafi, bangunin de Akbar sama Semar! Suruh cuci muka dan sarapan.” Perintah bi Heni kepada si sulung.
Mendengar perintah itu, ia bergegas mengemas sejadah dan membangunkan adik-adiknya.
Dari bilik langit, gulita pergi membawa oase cahaya dan mengantarkan terang. Di teras rumah panggungnya keluarga kecil itu memandangi butiran hujan dengan menyantap sepiring pisang goreng. Tiba-tiba motor trail datang dengan pengemudi yang berbalut jas hujan. Ternyata ia adalah suaminya bi Heni, bernama Mang Hendar.
“Horee ayah pulang.” Sahut si bungsu yang bernama semar.
“Di gunung hujan juga gak Yah?” tanya Bi Heni.
“Iya Mah, dari kemaren hujan aja, makanya ayah maksain pulang.” Balasnya.
Dengan sigap Bi Heni membawakan secangkir kopi hangat untuk suaminya. Mereka saling berceloteh menikmati suasana pagi dalam hujan.
Rumah panggung di lereng lembah itu, sebenarnya adalah sebuah warung yang kemudian di tambahi dengan ruang kamar. Warung itu berada di pinggir jalan raya, dangan pemandangan gunung di depannya, dan lembah di belakangnya. Kaki warung itu di sanggah dengan kayu-kayu pada punggung lembah.
Suasana pagi itu sehangat kopi yang dihidangkan. Kehangatannya lahir dari keceriaan ketiga putra mereka. Namun, kehangatan itu tetiba berubah menjadi suasana kalut seketika. Gunung kecil di depan warungnya memuntahkan kerikil dan lumpur tanpa aba-aba.
“Longsoooooorrr!” teriak mang Hendar.
“Allahuakbar!” Sahut Bi Heni Panik.
Tanpa pikir panjang, Bi Heni dan mang Hendar menarik tangan anak-anaknya dan berlari menuruni lembah. Deburan lumpur seakan mengejar arah mereka, setiap tanah yang mereka injak seakan mengikat kaki mereka. Lentur dan dalam seperti itulah kontur tanah saat itu.
“Yah, dimana kita harus sembunyi?” tanya Bi Heni sambil menangis.
“Disini aja, di bawah pohon pisang.” Balasnya.
“Ayo ke kandang ayam biar anak-anak gak kedinginan!” ajak Bi Heni pada suaminya.
“Jangan disini saja!” balas suaminya menegaskan.
Si kecil semar mulai merengek ketakutan, ia melihat dengan jelas bagaimana muntahan lumpur mengarah padanya.
Dalam persembunyian itu, mereka tak henti menengadahkan do’a. Lima menit berselang dalam persembunyian, mereka menyaksikan tanah bergesar pada kandang ayam di sebrangnya. Mereka semakin panik, anak-anaknya menangis bersahutan.
“Ya Allah, jika hari ini kami harus mati, maka sahid kan kami.” do’a Bi Heni amat pasrah.
Satu lokal kandang ayam terbawa arus longsor dengan cepat di hadapan mata mereka. Mereka mulai bingung, air mata Bi Heni melucur senada dengan luncuran air hujan.
Ketiga anaknya mulai kedinginan dalam persembunyian, kulit si bungsu mulai menghijau. Selang tiga puluh menit di bawah pohon pisang, mereka memutuskan untuk naik dari lembah.
Dari atas lembah mereka mulai memutuskan langkah lain untuk menyelamatkan diri.
“Hayu kita ke rumah nenek!” ajak Mang Hendar.
Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke kampung Cinyiru. Namun, di tengah perjalanan mereka di kejutkan dengan longsoran di gunung Citagogag. Semburan air dan lumpur menghujani jalan mereka. Mereka amat panik.
Anak keduanya yang bernama Akbar hampir di tarik arus sungai, tetapi dengan sigap bi Heni menarik tangannya. Sambil menjerit ketakutan mereka putar arah menuju gubugnya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melewati tanah lumpur bekas longsoran tadi.
“Rafi, pegang tangan Akbar. Pegang yang kuat jangan dilepaskan!” perintah Bi Heni dengan tegas.
Mang Hendar berada paling depan dengan memegang tangan kanan istrinya. Bi Heni berada di tengah dengan menggendong anak bungsunya. Anak sulungnya Rafi berada di urutan ketiga dengan berpegangan pada ibunya. Pada barisan terakhir, ada anak kedua mereka bernama Akbar yang memegang erat tanggan kakanya.
Selangkah demi selangkah mereka mulai menapaki kubangan lumpur yang dalamnya selutut pada tubuh bi Heni, dan sedada pada tubuh Akbar anak keduanya.
Melihat lumpur yang hampir menenggelamkan Akbar, Mang Hendar akhirnya menggendong Akbar pada punggungnya. Mereka melewati kubangan lumpur itu dengan deraian air mata yang seperti lupa untuk berhenti.
Baju mereka kuyup oleh sang hujan, tangan semar semakin dingin, dan bibir mungil si bungsu nampak membiru.
“Selamatkan anak-anaku ya Allah.” Gumam Bi Heni dalam hati.
Perjalanan itu begitu emosional, tiga puluh menit mereka lewati amat terjal. Noda lumpur dan basah kuyup membungkus diri mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di kampung Jaha yang aman dari longsoran.
Banyak warga menyambut mereka ada yang tersenyum haru, namun tak banyak pula yang meneteskan air mata. Salah seorang warga memberikan tumpangan untuk istirahat dan makan.
Kejadian ini, adalah momen yang akan terkenang dalam labirin ingatan mereka. Melewati pagi yang di awali dengan sepiring pisang goreng dan di akhiri dengan semburan lumpur muntahan perut gunung.
Bi Heni tak pernah menyangka jika ia bisa melewati ujian ini dengan keselamatan yang sempurna. Sekali dalam seumur hidupnya, ini adalah perjalanan yang paling terjal. Seperti berperang dengan ajal, tetapi Tuhan memberinya peluang untuk hidup. Begitulah yang ia rasakan. Setiap hujan datang ia di hantui episode yang membawa gelisah dalam hatinya.
Dari hal ini ia belajar, jika Tuhan memberinya kesempatan untuk hidup, maka harus ia gunakan untuk segala kebaikan. Bersyukur dan berterimakasih adalah upaya ia melanjutkan hidup dari sisa bencana 1 Januari 2020.
-Sekian-



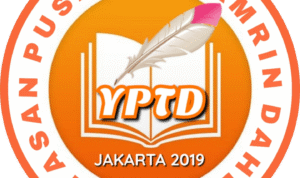



Subhanallah, setiap orang mendapat cobaan yg berbeda. Alhamdulillah Allah masih melindungi keluarga bi Heni. Jangan lupa bersyukur bagaimana pun cobaan kita. Tak sadar terisak.
Cerita yang luar biasa. Enak dibacanya dan membawa perasaan pembacanya. Pengen buat cerpen, tapi belum bisa.