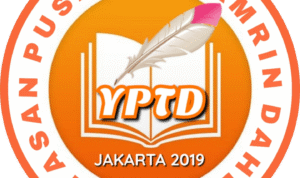8 | Hari Kesembilan Sejak Kematian
“Jangan ke sana! Kamu di rumah saja, Rama!”
Rama tidak mengindahkan teriakan neneknya yang berusaha mengejarnya. Anak yang masih memakai sarung itu berlari menyusuri jalan depan rumahnya. Di sebuah tikungan dia mengambil arah kanan lalu terus menyusurinya. Dia pun berlari menyusuri jalan setapak berlapis paving block itu secepatnya. Di sepanjang larinya air mata setia menemani kesedihannya. Matanya yang telah sembab bahkan tidak peduli dengan debu selepas ashar yang terus bergerak menuju senja. Langkahnya terus menembus iring-iringan tangisan selepas salat jamaah di masjid desanya. Langkah demi langkah pun berhasil menerobos sampai di barisan paling depan sebelum masuk pintu gerbang kompleks peristirahatan yang ada.
Terdengar suara doa-doa dipanjatkan di sore yang semakin redup itu. Kekhusyukan munajat terlihat dari wajah-wajah yang menunduk haru. Gurat kehilangan terlihat jelas di wajah-wajah yang mencoba ikhlas melepas kepergian yang terkesan terburu-buru. Namun, tidak demikian halnya dengan Rama yang seolah tidak akan mampu menghadapi kenyataan baru. Lebam matanya kosong menatap tanah merah yang masih baru. Anak kecil itu telah kehabisan isak sejak memperoleh kabar bapaknya tidak bisa tertolong lagi hingga akhirnya terbujur kaku. Dekapan hangat mamaknya, genggaman erat Imah Inges dan teman-temannya belum cukup mampu membendung kesedihannya yang masih enggan berlalu. Dan, batasnya kesedihannya menabrak dinding kesadaran yang semakin semu. Tubuh Rama tiba-tiba tergolek di sebelah penanda berupa kayu.
Tubuh tegap dan tinggi besar itu kini seolah kehilangan alasan untuk tetap bertahan hidup. Dia sedang jatuh sejatuh-jatuhnya jatuh dalam cahaya redup.
“Sadarlah, Nak!” teriak mamak Rama sambil berusaha menggerak-gerakkan kepala Rama agar matanya tidak lagi kosong. Usaha itu belum membuahkan hasil, tetapi justru melahirkan lolong. Tatapan anak semata wayangnya itu masih belum menemukan apa yang ingin dilihatnya atau sekadar minta tolong.
Sore semakin tua ketika para pemgantar jenazah meninggalkan lokasi pemakaman. Di sekitar tanah merah basah itu masih duduk Rama bersama beberapa orang terdekatnya yang merasa kehilangan. Rama masih membisu dalam kekosongan tatapan. Tenaganya seperti hilang bahkan sekadar untuk melakukan sebuah kedipan. Segala yang dimilikinya seolah telah ikut terkubur bersama jasad bapaknya yang telah dimakamkan.
“Bapak … Rama pengin ikut Bapak.”
Dengan bantuan Rajab, Rama akhirnya berhasil diajak pulang. Di rumah mereka, para pengungsi telah menunggu mereka datang. Aroma duka melingkupi halaman luas yang beberapa bagiannya telah berdiri tenda warna-warni berbagai ukuran sejauh mata memandang. Di tengah halaman, beberapa orang menggelar tikar panjang. Dan, sesuai adat masyarakat Lombok, hingga sembilan hari ke depan akan dilaksanakan tahlilan dengan kelompok pengajian yang diundang.
Dengan dikomandoi oleh Rajab, sembilan hari pun berlalu tanpa hambatan. Namun, tidak dengan Rama yang belum bisa mengikhlaskan kehilangan. Jiwa raganya benar-benar telah terguncang tak keruan. Belum pulih trauma gempa yang mengubur ingatannya tentang keseruan memainkan alat-alat kecimol, bumi justru mengubur harapan kesempatannya membahagiakan bapaknya di masa depan.
Di hari kesembilan itu Rama termangu sendirian di depan reruntuhan sanggar seni milik bapaknya. Di dalamnya perlengkapan kecimol seolah tak bisa lagi dikenalinya. Gitar kesayangannya hancur berkeping-keping tanpa sisa. Drum yang biasa ditabuh Ipang Jering pun tidak jauh berbeda. Termasuk juga sound system yang biasa didengarnya. Perlengkapan yang selalu menjadi kesayangan Rudi Solong itu pun bernasib tragis tak terkira. Pecahan-pecahan berserakan bersama harapan Rama untuk tetap menjaga kecimol sebagai bagian dari tradisi daerahnya. Rama tahu kecimol bukanlah kesenian asli daerah tempat lahirnya, tetapi baginya itu adalah bagian kekayaan budaya yang harus dilestarikan olehnya. Entah bagaimana caranya.
“Kamu mau sanggar seni ini dibangun lagi, Nak?”
Sebuah pertanyaan tiba-tiba mengejutkannya. Dia menoleh ke arah datangnya suara dan melihat mamaknya telah berdiri di belakangnya.
“Iya, Mak. Rama juga pengin jadi orang yang bermanfaat kayak Bapak di bidang musik,” jawab Rama pelan dan seolah tertahan.
Mamaknya mengelus rambut tebalnya dan berkata, “Kalau kamu mau, besok setelah bencana selesai Mamak akan bangunkan sanggar seni yang lebih bagus lagi. Bagaimana, Nak? Kamu mau?”
Rama tidak langsung menjawab. Dia terdiam dalam tatap. Ingatan demi ingatan tentang kecimol yang dirintis bapaknya begitu membekas dalam senyap.
“Ndak usahlah, Mak. Timbang dipakai untuk membangun sanggar seni lebih baik untuk bantu tetangga memperbaiki rumahnya. Mereka jauh lebih membutuhkan.”
Tanpa disadari air mata Mamak Rama menetes mendengar jawaban itu. Dia sendiri heran kalau anak sekecil ini bisa berpikiran dewasa seperti itu. Dia percaya kalau situasi dan kondisi pasca bencana yang telah mendewasakan sikap dan perilaku.
“Insyaallah nanti ada cara, Mak. Saya akan berusaha sendiri untuk membangun kembali sanggar seni ini. Saya hanya butuh doa restu Mamak untuk saat ini.”
Hati mamak Rama seolah tertusuk dengan kata-kata anak kecilnya dengan jujur. Dia sama sekali tidak menduga kalau ternyata anaknya lebih dewasa cara berpikir dibanding usianya yang masih bau kencur.
“Bapakmu pasti bangga, Nak,” batinnya sambil berlalu dan meninggalkan Rama di tempat itu.
Dalam kesendirian Rama kembali merangkai angan-angan. Tentang rencana yang akan dia lakukan. Saat sedang mengedarkan pandangan tiba-tiba ada suara lain mengejutkan.
“Rama … Ayo makan dulu! Kakak sudah masak makanan kesukaanmu. Ayo!”
Gendang telinganya menangkap suara merdu menyapa dalam sunyi. Suara yang selama ini tak kenal lelah membantu menguatkan keluarganya setiap hari. Dia mengenali suara itu lewat kidung-kidung yang sering didengarnya di sanggar seni. Sebuah tempat ternyaman baginya dan teman-temannya menempa kemampuan untuk menemukan jati diri.
Rama tidak kunjung menyahut. Mulutnya seolah telah dikunci oleh beberapa pertanyaan yang masih tertutup kabut. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kelak waktunya tiba, dia bisa mengungkap semua tanpa takut.
“Sepertinya aku bisa mengawalinya dari sini,” batinnya sambil membalikkan badan.
Sepasang bola matanya menangkap sesosok gadis cantik yang sedang memamerkan senyuman. Senyuman tulus yang akhirnya dia balas dengan sebuah pertanyaan.
“Kak Imah jadi menikah dengan Paman Rajab?”
Rama melihat senyuman gadis itu mendadak lenyap begitu saja. Namun demikian dia sama sekali tidak menyesal telah bertanya. Setelahnya keheningan melanda untuk sementara, Rama merasakan genggaman di jari-jari tangannya. Dia menurut ketika jemari lentik itu menariknya perlahan-lahan menuju teras depan rumahnya.
Di teras beralas marmer berdebu itu, keduanya duduk berdua. Rama menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Sementara di samping kanannya gadis pemilik suara emas itu meletakkan kedua tangannya ke belakang tubuhnya. Keduanya memandang jauh ke halaman yang penuh warga. Hiruk pikuk pengungsi sama sekali bukan halangan bagi mereka untuk membiarkan angan dan ingatan berkelana.
Hingga akhirnya suara Imah Inges memecah batu keheningan.
“Rama … Kamu kenapa nanya itu?”
Rama pun menyahut sambil membuka kedua tangannya meletakkannya di atas kedua pahanya.
“Saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya, Kak. Tapi aku hanya ingin tahu keseriusan Kak Imah dengan Paman Rajab.”
Imah Inges menarik napas panjang. Dia seperti sedang menyusun kata-kata agar bisa dipahami oleh Rama yang menunggu jawaban dengan tenang.
“Kakak memang pernah salah telah meninggalkan lelaki itu demi lelaki lain. Waktu itu Kakak baru kelas satu SMA dan memang hendak menikah dengan lelaki lain. Namun almarhum bapakmu yang sudah Kakak anggap seperti bapak sendiri menolak. Beliau menasehati kalau Kakak masih terlalu muda untuk menikah. Beliau akhirnya berhasil meyakinkan Kakak bahwa masih banyak mimpi besar yang ingin Kakak ubah menjadi nyata. Beliau juga berpesan agar Kakak meneruskan sekolah sampai lulus kuliah.”
Rama melihat Imah Inges kembali menarik napas panjang. Dia juga melihat ada telaga di mata Imah Inges yang tenang. Cukup lama keheningan kembali mengakrabi mereka berdua yang saling pandang.
“Almarhum dengan persetujuan mamakmu juga bahkan siap membiayai Kakak hingga lulus kuliah. Sedangkan Kakak secara tidak langsung terikat kontrak sebagai penyanyi kecimol di grup bapak. Dan, sekarang Kakak sudah hampir menyelesaikan kuliah. Artinya perjanjian itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, Rama. Tapi tidak bagi Kakak. Sampai kapan pun perjanjian itu akan tetap menjadi bagian terindah dalam kehidupan Kakak.”
Rama melihat gurat kesedihan di wajah gadis berbibir penuh dan menawan. Dia ikut pun ikut terlarut dalam lautan luka ingatan.
“Maafkan saya, Kak. Saya ndak ada maksud membuat Kakak sedih lagi,” kata Rama.
Mendengar kata-kata Rama, Imah pun berkata, “Sudahlah, Rama. Ndak papa, kok. Mending sekarang kita fokus pada rencana semula. Bagaimana?”
Rama melihat binar bahagia telah melingkupi wajah Imah yang jelita dan rupawan. Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk mencari kepastian.
“Kakak yakin mau lanjut? Bagaimana dengan Paman Rajab? Bukankah Kakak tahu kalau Paman Rajab orang dekatnya Pak Ahmad?” Rama bertanya sambil menatap kedalaman mata Imah.
Di bening kedalaman mata indah itu Rama sama sekali tidak menemukan ada sedikit pun keraguan. Gadis berkerudung cokelat gelap itu sepertinya telah memikirkan segala risiko dan kemungkinan-kemungkinan dengan matang penuh perhitungan.
“Yakin! Kakak tahu kalau Kak Rajab adalah orang terdepan Pak Ahmad yang mengusulkan peraturan desa itu. Kamu tenang saja. Kak Rajab biar aku yang urus. Sebisa mungkin Kakak akan buat dia berbalik mendukung kita,” jawab Imah sambil tersenyum.
Rama menangkap itu sebagai sebuah keyakinan. Dia pun terbawa energi positif keyakinan yang ditebarkan. Dia membayangkan keberhasilan rencana mereka berdua bersama teman-temannya di kelak kemudian.
Hari menjelang siang ketika keduanya berjalan beriringan menuju dapur umum. Di sana beberapa orang perempuan warga desa terlihat menyiapkan makan siang termasuk buah berupa mangga yang telah ranum. Di depan pintu tenda dapur umum, Rama melepas Imah masuk dengan senyum. Dia segera bergegas menemui teman-temannya yang telah menunggunya di sudut lain; masih dengan senyum dikulum.
Rudi Solong sedang mendongeng ketika Rama tiba. Sedangkan Ipang Jering bergabung dengan anak-anak lainnya yang duduk berbaris dengan rapi mendengar cerita. Sesekali terdengar gelak ketika Rudi Solong bercerita atau melakukan gerakan sesuai isi cerita. Rudi Solong yang memang pandai bicara dan memiliki selera humor yang lumayan membuatnya tidak kesulitan menerjemahkan kata-kata. Terlebih dengan tingkahnya yang seringkali membuat orang tertawa semakin mengukuhkan kemampuannya.
Hampir dua bulan sejak kejadian gempa berskala 7,0 Skala Richter itu, mereka bersama Imah Inges mulai berusaha memulihkan trauma anak-anak di pengungsian. Masing-masing diberikan tugas sesuai kemampuan. Rudi Solong bertugas mendongeng, Ipang Jering bertugas membacakan cerita, sedangkan Rama dan Imah bertugas menjadi penyanyi dan gitaris sebagai hiburan. Selain itu, Rajab pun tidak ketinggalan. Sebagai orang paling tua di kelompok itu, dia memimpin kegiatan mengaji dan berdoa. Termasuk memimpin doa bersama saat acara ‘nyiwaq’ setelah sembilan hari meninggal dunia Bapak Rama. Berkat mereka suasana pengungsian bukan lagi sebuah tempat yang mengerikan dan berbahaya.
***