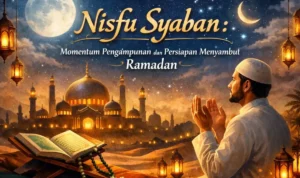Hai sobatku saya akan kembali mengulik kisah petualanganku ya. Sebelumnya, saya ingin mengajak anda sekalian untuk membangkitkan kenangan-kenangan terindah ataupun kenangan yang paling konyol dalam kisah petualangan anda, ketika menginjakkan kaki pertama kali di tanah rantau.
Bagaimana perasaan yang anda alami? Tegang, itu sudah pasti. Karena saya pun pernah berada dalam fase tersebut.
Pagi itu, tepatnya bulan Juli 2014, saya mulai mencicipi makanan khas Jawa Timur yakni; Rawon.
Maaf, jika saya tidak bisa menjelaskan panjang kali lebar seputar makanan khas ini ya. Karena ini hanya sebatas pengantar, sebelum saya masuk pada topik pembahasan saya yakni; “Kelabu Bulan Juli 2014.”
Terik matahari serta deburan polusi udara bertebaran di setiap pojok kota pahlawan Surabaya, saya duduk tersipu di salah satu rumah makan yang letaknya kurang lebih 20 km dari bandara internasional Djuanda.
Sebotol teh pucuk menetralisir hawa panas kota pahlawan. Tanpa terduga, salah satu pengunjung rumah makan itu mendekati saya dan bertanya; “mas sampeyan saking Jowo?”
Saya memilih untuk tidak meladeni pertanyaan dari lelaki tersebut. Akan tetapi, lelaki itu terus bertanya. Akhirnya, saya berusaha untuk meladeninya dengan jawaban yang singkat; Maaf pak, bolehkah anda mengulangi pertanyaan yang barusan?
“Ow nggeh. Begini ya mas, terkait pertanyaan saya itu tentang apakah anda berasal dari Jawa?”
Saya pun menarik nafas, sembari merasa lega. Karena saya bisa menjawab dengan bahasa Indonesia.
“Tentunya, saya berasal dari Timor, NTT.” Memangnya pak tidak melihat kulitku yang sao matang ini?” Celotehku dalam hati.
Setelah saya menelusuri jejak tapaknya, saya pun menemukan asal muasal (kausalitas) dari lelaki tersebut. Dan ia berasal dari Kalimantan Timur. Namanya “Cogito.”
Nama yang paling fenomenal. Karena nama ini mengingatkan setiap orang yang pernah berhubungan intim dengan bidang filsafat dan lebih tepatnya dengan ucapan tokoh renaisans asal Prancis yakni; Rene Descartes; “Cogito Ergo Sum: Aku berpikir karena aku ada.”
Perdebatan Sengit di Kota Pahlawan
Apa jadinya, jika dua orang yang barusan bertemu dan masing-masing ingin menonjolkan kelebihan budayanya?
Yang pasti kedua orang tersebut akan masuk dalam ranah superego. Ya, begitulah yang saya dan Cogito alami.
Kronologisnya begini sobatku. Setelah “say-hello” di rumah makan tersebut, ternyata mobil yang kami tumpangi menuju kota pendidikan Malang itu pun sama.
Sepanjang perjalanan, kami sharing seputar kebudayaan kami berdua. Terkadang, saya melebih-lebihkan budaya saya. Begitu pun dengan Cogito. Akhirnya, kami memasuki fase perselisihan yang tidak ada solusinya.
Keadaan Memaksa Kami Untuk Diam
Antara saya dan Cogito belum mencocoklogikan psiko emosional kami. Karena kami masih belum berani untuk melepaskan ego dan superego kami.
Meskipun dalam bidang humaniora mengatakan bahwa untuk mendamaikan kedua orang yang berbeda budaya adalah berani melepaskan prasangka.
Apakah antara saya dan Cogito masih hidup dalam prasangka? Bisa ya dan bisa tidak. Jawabannya tergantung setiap pribadi.
Jujur, saya masih hidup dalam prasangka. Akibatnya, pintu hati saya selalu tertutup untuk melihat kebenaran di luar kebudayaanku. Saya harap, sobatku jangan mengikuti caraku ya. Karena hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai “Bhineka Tunggal Ika.”
Saya yakin juga bahwasannya Cogito pun masuk dalam lingkaran negatif ini. Bukti empirik telah menunjukkan dengan sangat jelas yakni; perjalanan dalam keadaan diam.
Padahal, saya masih memiliki segudang pertanyaan yang masih tersimpan di dalam kalbuku. Tapi, demi kenyamanan kami, saya memilih untuk mengalah. Mengalah bukan berarti tidak punya nyali. Tetapi, demi nilai-nilai kemanusia dan semangat berkelana.
Itulah kekonyolan saya dan Cogito di awal pertemuan. Dan saya pun menamakan pertemuan itu dengan sebutan “Kelabu bulan Juli 2014.”
Bersambung