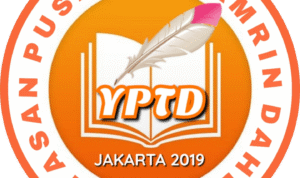9 | Bersama Menyembuhkan Luka
“… Mungkin Tuhan mulai bosan. Melihat tingkah kita. Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa …”
Sederet lirik yang diciptakan oleh Ebiet G. Ade itu menyayat terlantun merdu dari bibir Imah. Rama yang mengiringi dengan petikan gitar tak kuasa menahan air mata serupa bah. Tidak terkecuali Ipang Jering dan Rudi Solong yang seolah memahami hikmah. Mereka berdua terlihat bertatapan mencoba saling menguatkan agar tidak lagi resah. Tidak terkecuali dengan anak-anak yang berada di bawah tenda biru beralas karpet merah. Mereka ikut larut dalam kesedihan yang ditebarkan lewat lagu yang menggugah. Namun, itu hanya sementara guna mengetuk kesadaran bahwa semua yang terjadi harus diikhlaskan dengan tabah.
Benar saja. Tidak butuh waktu lama bagi anak-anak itu untuk kembali bangkit seperti semula. Terlebih saat petikan gitar Rama mengiringi lirik lagu anak-anak yang disenandungkan oleh Imah, sang biduanita. Semua anak-anak spontan ikut bernyanyi gembira. Mereka seolah lupa bahwa mereka telah menjadi korban bencana. Saat ini yang ada hanya gembira dan ceria.
Sore menjelang ketika mereka diminta untuk membubarkan diri dan bersiap untuk mengaji. Rama dan yang lain berkumpul dan dengan dipimpin Imah Inges mereka melakukan evaluasi.
“Menurut kalian kalau besok kita ganti format acara bagaimana?” tanya Imah sambil membetulkan letak kerudungnya.
Rama dan dua orang temannya menganggukkan kepala. Anak lelaki pemetik gitar itu belum punya ide apa-apa. Yang dia tahu adalah memetik gitar saja. Tidak beda dengan kedua temannya. Ipang Jering dan Rudi Solong terlihat menggelengkan kepala.
“Jadi besok sore cukup kita adakan permainan saja. Nanti gampang, Kakak yang nyari permainannya apa saja. Oke?!”
“Oke!” Terdengar teriakan penuh semangat dari ketiganya.
Keesokan harinya saat sore tiba di bagian halaman yang rata, Rama menggelar sebuah papan permainan. Papan permainan dari bahan vinyl berbentuk persegi itu memiliki dua bagian. Di bagian dalamnya terdapat kotak bergambar tentang sembilan nilai, yaitu kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerjasama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian. Ipang Jering dan Rudi Solong membantu Rama dengan mengatur tumpukan potongan kertas berwarna merah dan putih di bagian tengah papan permainan. Sementara itu Imah Inges mengumpulkan beberapa anak untuk memulai permainan.
“Hore! Hari ini kita akan melakukan permainan baru! Sebuah permainan yang disebut SEMAI. Ada yang tahu ndak?” Imah Inges bertanya peserta permainan.
Tidak ada satu pun peserta yang tahu tentang permainan ini. Bagi mereka ini adalah hal baru yang menarik untuk diketahui.
“SEMAI ini kepanjangan dari Sembilan Nilai Antikorupsi. Permainan ini digagas oleh SPAK atau Saya Perempuan Antikorupsi. Jadi, kita bermain sekaligus belajar. Kalian siap?”
Jawaban kesiapan terdengar bergemuruh di sore yang kian lusuh. Semburat jingga di langit barat sedikit memudar oleh awan penuh. Namun, tidak dengan peserta permainan yang memiliki niat teguh.
Rama yang tergabung di salah satu kelompok tersebut terlihat antusias ketika Imah Inges menjadi fasilitatornya. Dia dan teman kelompoknya memperhatikan penjelasan yang diberikan dengan saksama setiap detailnya. Demikian halnya dengan Ipang Jering dan Rudi Solong serta anggota kelompok mereka.
“Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas, kan?”
Mereka pun menjawab dengan kompak. Jawaban itu sekaligus sebagai tanda bahwa permainan sudah bisa dimulai serentak. Melalui sistem undian, kelompok Rama nendapat giliran pertama untuk mengambil kartu berwarna putih di tengah kotak. Rama meminta salah seorang temannya untuk membacakan sebuah situasi dengan lantang setengah berteriak.
“Aku dibelikan tas sekolah baru di luar negeri oleh ayah. Setiap hari tas itu kupamerkan pada teman-teman. Aku ingin teman-temanku tahu bahwa aku punya tas baru. Perilaku ini tidak sesuai dengan nilai?”
Rama mengajak teman-temannya berdiskusi untuk menentukan pilihan jawaban. Setelah sepakat, Rama meletakkan kartu itu di atas kotak bergambar anak laki-laki sedang naik sepeda mini dengan tulisan ‘kesederhanaan’. Anggota lainnya pun bertepuk tangan karena telah yakin dengan jawaban. Dengan sabar mereka pun menunggu Imah Inges kembali memimpin permainan.
“Apakah jawaban kelompok satu betul?” Imah Inges bertanya kepada kelompok dua.
Dengan tegas, Ipang Jering pun menjawab, “Betul, Kak!”
Imah Inges menampung tanggapan kelompok dua, lalu bertanya kepada semua peserta, “Mengapa situasi tersebut tidak sesuai dengan nilai kesederhanaan? Ada yang tahu?”
Untuk beberapa saat Rama dan anak-anak lainnya terdiam. Mereka masih mencari jawaban yang tepat dengan berpikir dalam-dalam. Hingga akhirnya salah seorang anggota kelompok satu menjawab, “Eh … Mungkin karena tas yang dibelikan ayahnya terlalu mahal untuk ukuran anak sekolah, Kak.”
“Jawaban yang sangat bagus. Ada yang bisa melengkapi?” Imah Inges kembali melemparkan pertanyaan kepada peserta.
Kali ini Rudi Solong tidak mau kalah. Dengan mantap dia menjawab, “Karena anak itu tidak mau memberikan tasnya kepada kita yang lagi membutuhkan, Kak.”
“Ha ha ha. Dasar kamu, Solong. Maunya gratisan saja,” timpal Ipang Jering yang tidak bisa menyembunyikan tawanya.
Gelak pun memecah di penghujung sore yang semakin buram terasa. Tidak terkecuali Imah Inges yang kemudian memberikan penjelasan kepada mereka semua. Sebelum permainan diakhiri, kelompok dua diberikan kesempatan untuk mengambil kartu merah sebagai hukuman karena tidak bisa menjawab dengan tepat atas situasi yang dibaca. Dengan sportif kelompok dua pun menyelesaikan hukuman untuk mereka.
Jingga di ujung senja hampir sirna. Azan Magrib sebentar lagi akan berkumandang memenuhi semesta. Rama dan yang lainnya pun bergegas mengakhiri semua. Selanjutnya mereka bersiap-siap ke masjid untuk beribadah dan mengaji bersama.
Sepeninggal mereka, di pengungsian hanya tinggal kaum perempuan dan tetangga yang beragama Hindu. Mereka saling bantu membersihkan alas terpal dan menyiapkan makan malam agar tepat waktu. Setelah semua siap mamak Rama memanggil Imah Inges untuk duduk bersama di kursi kayu berwarna hitam berhias potongan telur yang biasa disebut dengan kerajinan ‘cukli’ itu. Mereka berdua saling berbalas senyum tanpa ragu.
“Imah… Terima kasih sudah membangkitkan lagi semangat anak-anak di pengungsian. Terutama Rama,” kata mamak Rama.
Imah tersenyum lalu berkata, “Ndak papa, Mak. Ini sudah kewajiban Imah untuk bantu adik-adik. Semua berkat Kak Rajab yang sudah mau mengorbankan waktunya untuk mengkoordinir semua kegiatan.”
Mamak Rama sejenak terdiam saat Imah Inges menyinggung nama Rajab. Dia paham betul dengan konflik yang sedang terjadi antara keluarganya dengan pria muda yang telah lama dikenalnya itu. Setelah menarik napas perempuan yang masih terlihat cantik di usia menjelang lima puluh tahun itu berkata, “Ngomong-ngomong tentang Rajab … Kamu pasti sudah tahu semua tentang konflik keluarga kita, kan, Mah?”
Imah Inges menganggukkan kepala. Dia masih menunggu mamak Rama sekaligus mamak angkatnya itu mengungkapkan semua yang ingin diketahuinya.
“Apa kamu juga tahu sejauh mana kedekatan Rajab dengan almarhum Bapak?” Mamak Rama bertanya dengan tatapan tajam ke arah Imah Inges.
Imah Inges pun akhirnya menjawab, “Saya belum tahu, Mak. Tetapi saya pasti akan mengetahuinya. Cepat atau lambat saya akan membuat Kak Rajab mau bercerita tentang rahasia kedekatannya dengan almarhum bapak.”
“Terima kasih, Imah. Mudahan ndak butuh waktu lama untuk itu. Mamak sebenarnya sudah sejak lama menyimpan ini. Rasanya ndak sanggup lagi untuk berteka-teki,” kata mamak Rama yang kemudian matanya menerawang.
Demi melihat kekosongan tatapan mata perempuan itu, Imah pun berusaha menguatkan. Gadis belia itu kemudian mengalihkan pembicaraan. Dia tahu kalau mamak angkatnya ini sangat pandai berjoget dan menciptakan gerakan.
“Setelah sekian lama ndak joget, Mamak masih bisa joget ndak? Pasti sudah lupa. He he he.”
Mamak Rama tersenyum mendengar pertanyaan yang menurutnya konyol itu. Bagaimana dia bisa lupa setiap detail gerakan, sudah puluhan tahun dia menekuni secara profesional. Entah sudah berapa ribu kali dia pentas. Entah berapa ribu tempat dia kunjungi untuk menunjukkan kemampuannya. Meskipun banyak yang menghinanya, tetapi baginya justru itu pemacu untuk membuktikan siapa dirinya. Waktu pun mendukungnya untuk memberikan bukti. Pentas jogetnya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Apa pun dan di mana pun dia tetap menjunjung tinggi harga diri dan keluarganya. Terlebih beberapa pentas terakhir, dia bahkan mendapat undangan dari gubernur Nusa Tenggara Barat untuk unjuk kebolehan di acara kelas internasional. Namun, stigma negatif tidak serta merta luntur. Anggapan tukang joget sebagai pembawa aura negatif tetap saja melekat. Hal ini membuatnya pasrah. Hingga suatu hari anaknya memintanya untuk berhenti. Dan, bencana gempa seolah menjadi petunjuk bahwa dia harus berhenti. Tabungannya dan juga hasil mendarmakan diri pada kesenian lebih dari cukup untuk menghidupi keluarganya dan tetangganya yang masih mengungsi di halaman dan tanah kosong sekitar rumah miliknya.
“He he he. Kalau Mamak lupa joget sama artinya lupa sama darah dan daging sendiri, Mah.”
Imah Inges tersenyum lebar. Pancingannya berhasil. Tidak ingin umpannya dilepas, dia pun mengeluarkan jurus jitunya.
“Mamak yakin? Kalau yakin buktikan, dong!” Seru Imah Inges sambil mengepalkan tangan kanannya.
“Siapa takut? Ayok saja, sih, kalau Mamak. Kapan? He he he.”
Mendengar jawaban Mamak Rama, kepalan tangan Imah Inges melayang ke udara lalu turun dalam sekejap bersamaan dengan teriakan, “Yes!”
“Besok sore kita buktikan di depan anak-anak, ya, Mak. Sekalian siapa tahu ada di antara mereka yang mengikuti jejak Mamak sebagai penari terbaik. He he he. Bagaimana, Mak? Mamak siap?”
Tanpa menjawab, Mamak Rama tersenyum sambil menepuk dadanya pelan. Sepelan angin malam yang mulai berembus mengantarkan kesiagaan dan kewaspadaan terhadap gempa susulan.
Tanpa mereka sadari, di kejauhan sesosok pria diam-diam mengamati. Sebelum mereka benar-benar selesai berdiskusi, dia telah benar-benar pergi dalam sebuah teka-teki.
***